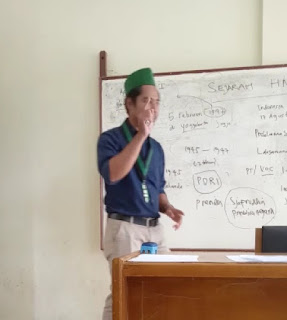UU KPK Perlu Direvisi
Oleh: Syahdi, S.H
(Pemerhati Hukum Tata Negara)
Tulisan ini adalah pandangan saya yang merupakan kelanjutan dari tulisan
saya sebelumnya “Menakar Revisi UU KPK
dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia”. Saya melihat bahwa revisi
undang-undang KPK adalah pilihan yang baik untuk memperkokoh sendi
ketatanegaraan khususnya di bidang penegakan hukum. Pertama perlu ditekankan
disini bahwa setiap undang-undang, undang-undang apapun selalu terbuka untuk
segala ide pembaharuan. Undang-undang bagaimanapun tetaplah produk manusia yang
tidak luput dari kekurangan, zaman yang berkembang dan pemikiran dalam
bernegara hukum yang semakin kaya, pula turut mempengaruhi bangunan kenegaraan
yang ideal. Walaupun soal ideal itu selalu mengalami perubahan, ideal hari ini
bisa saja tertinggal di waktu yang akan tiba.
Saya sadar bahwa pandangan saya dalam menyikapi revisi undang-undang KPK
ini akan dipandang sebagian orang bahwa saya secara langsung telah menempatkan
posisi saya melawan arus deras, besar dan bergemuruh di negeri ini. Sebab itu mungkin
saja saya akan dimarginalkan dan di sumpah serahi, dituduh yang bukan-bukan. Saya
menganggap hal itu wajar disebabkan beberapa hal, Pertama, perbedaan kemampuan
untuk menjelaskan masalah ini, dan, Kedua, mayoritas orang cenderung mengikut saja
kepada keputusan-keputusan diantara mereka. Saya menilai masalah ini (revisi
undang-undang KPK) tidak dalam kapasitas sebagai pengamat politik yang kadang kita
dapati ia tidak kukuh dalam memberi tanggapan dan gagap mencetus penilaian
daripada tanggapannya itu sendiri, kadang hanya mengikut saja kemana arus
mengalir.
Saya sebagai orang yang banyak bergumul dalam pemikiran kenegaraan
melihat bahwa ada kebaikan dalam revisi undang-undang KPK itu. Saya memandang bagaimanapun undang-undang KPK
perlu direvisi, tidak berarti bahwa saya menyetujui dengan sepenuh-penuhnya
pengaturan substansi oleh DPR dan Pemerintah. Beberapa hal justru perlu
diperdebatkan karena rupa-rupanya ia kita anggap bahwa cita penegakan hukum
yang fair menjadi sulit dan sangat kaku. Disamping itu tentu revisi yang
melemahkan kinerja law enforcement
oleh KPK harus kita tolak. Saya menjadi berat, dilematis tatkala keinginan
untuk menelaah persoalan ini ternyata terpaksa hanya mengandalkan bahan-bahan
yang tersebar di media. Bagi saya ini tak lebih daripada wilayah spekulasi yang
tidak jelas, menjebak dan membingungkan. Sebab kitapun tidak dapat memastikan
apakah benar bahan-bahan itu, sementara draft dari DPR maupun Pemerintah tidak
dipublikasikan. Menganalisa lalu memberikan penilaian berdasarkan kepada
bahan-bahan yang tidak jelas itu seperti mengawang-ngawang saja.
Andaipun itu
benar, saya melihat ada juga kebaikan di dalamnya, selainnya pula terdapat substansi
yang kontroversial, sehingga menggiring kita kepada banyak prasangka. Kesalahan pembentuk undang-undang tidak mensosialisasikan rancangan
undang-undang KPK menjadi biang dari semua kebingungan dan aksi massa. Secara umum
beberapa poin yang menjadi substansi revisi undang-undang KPK itu seperti,
eksistensi dewan pengawas (pengisian keanggotaannya dibentuk Presiden) dengan
segala kewenangannya (memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan, penyitaan),
status ASN semua pegawai KPK, rekrutmen penyelidik harus
dari kepolisian, kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan, yang
diletakkan dalam domain kekuasaan eksekutif, KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3 untuk
penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam waktu satu tahun, perlunya izin untuk
memproses pejabat negara tertentu, PPNS di KPK berada dibawah koordinasi penyidik Polri, pengangkatan
pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden pengetatan wewenang pencekalan bepergian
ke luar negeri.
1. Kebaikan
Dalam Revisi UU KPK
Beberapa hal yang ada kebaikan di dalamnya saya kemukakan
dahulu, yaitu:
a. Rekrutmen penyelidik dari kepolisian;
b. Kedudukan KPK dalam domain kekuasaan eksekutif;
c. SP3 untuk penyidikan dan penuntutan bagi perkara yang
tidak
selesai
dalam waktu satu tahun;
d. PPNS di KPK berada dibawah koordinasi penyidik Polri;
Tentang rekrutmen penyelidik harus dari kepolisian,
disatu pihak saya menilai memang ada sisi baiknya. Sebab dengan direkrut dari
kepolisian penyelidik pastinya tenaga handal yang berpengalaman melakukan
penyelidikan. Andai harus merekrut dari luar kepolisian agak berat juga sebab
KPK perlu melakukan serangkaian pelatihan atau pendidikan penyelidikan, jika
tidak tentu akan menyulitkan KPK dan menjadikan penyelidikan menjadi
terkendala. Kedantipun demikian, KPK tentu saja dapat merekrut dari mereka yang
memang telah berpengalaman juga dalam melakukan tugas penyelidikan dan
penyidikan misalnya mereka tersebutu adalah mantan anggota Polri. Disamping itu
dampak buruknya jika penyelidik harus berasal dari anggota Polri, maka
dikhawatirkan kepolisian dapat mengintervensi proses penegakan hukum melalui
penyelidiknya yang ditempatkan di KPK.
Kepolisian dapat saja mengontrol
atau mengendalikan dari luar proses penyelidikan sehingga penegakan hukum
menjadi tidak fair dan diskriminatif. Selanjutnya, terkait penataan tempat duduk KPK dalam
struktur ketatanegaraan. KPK sebagaimana telah disepakati dalam perubahan
undang-undangnya diletakkan sebagai bagian dari domain kekuasaan eksekutif.
Seperti halnya kejaksaan yang tegas dinyatakan dalam undang-undangnya sebagai
lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan dan pelaksana
putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan kewenangan lain yang diberikan
oleh undang-undang, KPK pun juga ditentukan sebagai lembaga pemerintah. Dalam
iklim ketatanegaraan kita saat ini, kejaksaan dan KPK memang dipandang
merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif sebab kewenangan atau tugas melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu dipandang adalah tugas-tugasnya
eksekutif (Pemerintah), bukan tugasnya legislatif maupun yudikatif.
Hal ini di dasarkan pada logika dan pemahaman doktrinal
terhadap anutan Trias Politica yang dipelopori oleh Charles
Louis desecondat Baron de La Breth et de Montesquieu atau yang lazim dikenal
Montesquieu. Bahwa kekuasaan dalam negara dibedakan, dibagi atau
dipisah-pisahkan kedalam tiga poros besar yakni legislatif sebagai pemegang
kebijakan legislasi yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan
eksekutif yang diciptakan dengan fungsi mengatur, mengelola, melakukan penertiban,
mewakili kepentingan hukum rakyat dalam sidang pengadilan untuk memperjuangkan
hak-haknya. Walaupun dalam bidang
eksekutif tersebut pemerintah dapat saja salah dan menjadi pihak yang digugat,
maka kepada rakyat juga dapat secara langsung berhadapan dengan pemerintah
memperjuangkan hak-haknya dalam sebuah forum khusus, kita mengenalnya
Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dalam forum pengadilan ad-hoc.
Poros ketiga dari Trias Politica adalah domain kekuasaan
yudikatif sebagai wadah bagi para pencari keadilan untuk menuntut dan
memperjuangkan hak-haknya. Dan hanya pengadilan lah yang berhak menjatuhkan
hukuman, bukan pemerintah dalam arti pemangku kekuasaan eksekutif. Untuk sementara
ini doktrin Trias Politica lah yang
menjadi basis argumentasi dan dasar bagi ide-ide ketatanegaraan khususnya dalam
hal ini keharusan meletakkan KPK dalam kekuasaan eksekutif. Seakan dalam hal
ini tidak tersedia atau telah tertutup ide untuk meletakkan kejaksaan, dan KPK
termasuk kepolisian dalam cabang kekuasaan yang lain selain eksekutif. Yang
penting ditekankan
adalah sekalipun KPK diletakkan dalam domain kekuasaan eksekutif tapi
kewenangan KPK dalam menegakkan hukum bukan bersumber dari Presiden tapi langsung
bersumber dari undang-undang, karena itu KPK tidak boleh di intervensi oleh
pemerintah atas dasar apapun juga yang bertentangan dengan cita penegakan hukum
di republik ini.
Tentang keharusan meletakkan
KPK dalam kekuasaan eksekutif ini, saya memandang secara berbeda persoalan ini
terutama kita perlu memikirkan ulang tentang kemungkinan adanya pilihan lain
yang lebih sesuai dalam teori fungsi negara selain yang kita anut sekarang ini
yaitu (yang sekarang) doktrin Trias Politica yang mengidealkan bahwa
kekuasaan negara mutlak harus dipisah-pisahkan kedalam tiga poros besar,
sekalipun tidak berarti antar kekuasaan itu dilarang berkoordinasi satu dengan
yang lain. Maksud saya, saya hendak mengajukan pemikiran lain walaupun bukanlah
tergolong pemikiran yang baru, tetapi pernah digagas dalam berabad-abad lalu di
Prancis, yakni tentang kemungkinan kita perlu memikirkan ulang untuk menerima
ide teori fungsi negara yang membagi atau memisahkan kekuasaan dalam negara
kedalam lima poros besar, yakni poros Defencie,
poros Financie, Politie, Bestuur dan Rechtspraak.
Demikian teori asalnya, tetapi untuk konteks kita di
negeri ini tidak mengapa agak sedikit kita kembangkan yaitu menjadi poros Regeling,
Bestuur, Rechtspraak, Politie, dan Financie (baca tulisan saya tentang
hal ini dalam “Rombak Ulang Struktur Ketatanegaraan, Trias Politica Perlu
Diganti”). Dalam doktrin ini Kejaksaan, KPK, Advokad dan Pengadilan lebih tepat
diletakkan kedalam poros Rechtspraak. Bahwa ditekankan
dalam doktrin lima poros kekuasaan ini masing-masing poros kekuasaan
kedudukannya sederajat dan independen dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya. Dengan demikian, KPK dan kita tidak perlu lagi khawatir
pemerintah sebagai penguasa di poros Bestuur akan mengintervensi atau
menggerogoti independensi KPK dalam penegakan hukum. Sebab pemerintah dan KPK
berada dalam poros yang berlainan dan tiap-tiap poros berkedudukan sederajat
satu sama lain. Dengan demikian saya menilai dengan doktrin lima poros
kekuasaan ini dapat lebih menjamin stabilitas kita dalam bernegara di republik
ini.
Berikutnya, tentang kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 terhadap penyidikan dan penuntutan bagi perkara yang
tidak selesai dalam waktu satu tahun. Ketentuan seperti ini menurut saya baik
sekali untuk diberikan kepada KPK, sehingga KPK benar-benar di dorong agar
efektif, berhati-hati dan cekatan dalam menegakkan hukum. Kita tidak ingin
kasus dan cerita-cerita memilukan di waktu lampau terulang lagi, seperti pada
masa berlakunya HIR (Het Inlands
Reglement) yaitu hukum acara di masa kolonial. Bahwa seseorang yang setelah
ditangkap tidak jelas ujung pangkal penyelesaian kasusnya, sementara ia terus
ditahan bertahun-tahun bahkan stres, dan meninggal dalam masa penahanannya itu,
sedangkan kasusnya belum juga mendapat kepastian penyelesaiannya. Hal ini jelas
sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tidak pantas bagi suatu
negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum berperilaku demikian. Karena
itu pemberian kewenangan SP3 ini penting dilakukan agar ada kepastian hukum
dalam menegakkan hukum prosedural.
Selanjutnya, PPNS di KPK berada dibawah koordinasi
penyidik Polri. Ketentuan seperti ini telah sesuai dengan pengaturan awalnya
yaitu dalam KUHAP. Bahwa memang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada
dibawah koordinasi penyidik Polri. Hanya saja daalm revisi undang-undang KPK
itu harus jelas bahwa penyidik Polri yang dimaksud adalah penyidik Polri di
KPK, atau penyidik yang berasal dari unsur kepolisian yang ditugaskan menjadi
penyidik di KPK. Jadi bukan penyidik Polri yang bertugas melakukan penyidikan
di institusi Polri, Melainkan ia telah ditugaskan, penugasannya dipindahkan di
institusi KPK. Penyidik Polri di kepolisian hanya menjalankan tugasnya dalam
cakupan tugas-tugas kepolisian, demikian pula penyidik Polri di KPK menjalankan
tugasnya atas nama KPK. Jadi tidak dipahami bahwa penyidik PPNS di KPK berada
dibawah koordinasi penyidik Polri di kepolisian, melainkan berada dibawah koordinasi
penyidik Polri di KPK. Penyidik Polri di KPK ini sebaiknya cukup disebut
penyidik saja, penyebutan dari unsur Polri hanya sekedar untuk membedakannya
dengan penyidik dari kalangan PNS atau penyidik PPNS.
2. Kelemahan
Dalam Revisi UU KPK
Beberapa
hal yang mempersulit, dianggap menghambat kinerja KPK yakni:
a. Eksistensi dewan pengawas (pengisian keanggotaannya dibentuk Presiden) dengan
segala kewenangannya (memberi izin untuk penyadapan, penggeledahan, penyitaan);
b. Perlunya izin untuk memproses pejabat negara tertentu;
c. pengangkatan pimpinan KPK dilakukan oleh Presiden;
d. Pengetatan wewenang pencekalan bepergian ke luar negeri;
e. Status ASN bagi semua pegawai KPK.
Pembahasan poin a sampai d saya bahas mengalir saja tidak dalam bentuk
poin-poin tersendiri. Agak sulit saya memutuskan menempatkan pembahasan tentang
dewan pengawas ini di sub pembahasan kelemahan revisi undang-undang KPK. Sebab
bagaimanapun ada juga sisi baiknya. Tentang keberadaan dewan pengawas KPK,
perlu dipahami disini, Pertama, fungsi dewan pengawas ini sangat
vital bahwa KPK diantaranya harus mendapat izin dari dewan pengawas untuk
melakukan penyadapan, termasuk izin untuk melakukan penggeledahan dan
penyitaan. Saya melihat keberadaan dewan pengawas ini memiliki potensi atau
kecenderungan yang membawa dampak sekurang-kurangnya kepada dua keadaan
yaitu, Pertama, dapat membatasi gerak langkah KPK sehingga
tidak maksimal dalam penegakan hukum.
Disini dewan pengawas dengan fungsi dan
seperangkat kewenangannya potensial dapat terjadi atau dapat saja dinilai
menghambat kinerja KPK dan menjauhkan KPK dari cita penegakan hukum yang luhur
untuk mengupayakan keadilan bagi segenap warga negara. Kedua, keberadaan
dewan pengawas dapat menciptakan penegakan hukum oleh KPK menjadi lebih
berwibawa. Untuk keadaan yang pertama, penilaian terhadap hal ini sangat
subjektif sifatnya. Baik-buruknya terutama dirasakan oleh KPK sebagai pihak
yang terkena dampak dari implementasi kebijakan dewan pengawas bila mana KPK
memandang kebijakan dewan pengawas tidak sejalan dengan konsepsi maupun cara pandang
penegakan hukum oleh KPK. Kendatipun bersifat subjektif, subjektifitas tersebut
selalu dapat diukur berdasarkan kriteria objektif untuk menentukan sejauh
manakah penilaian subjektif itu dapat sejalan dengan kriteria objektif
berdasarkan pengaturan dalam undang-undang.
Artinya, bukanlah penilaian
subjektif yang kosong yang dikesankan hanya mengikuti kehendak nafsu belaka
yang justru semakin menjauhkan dari cita penegakan hukum itu sendiri.
Pengukuran derajat subjektifitas ini baru hanya akan dapat dinilai ketika
terjadi beda pendapat atau perselisihan antara pimpinan dan/atau penyidik KPK
dengan dewan pengawas dalam proses penegakan hukum.
Andai demikian halnya maka menurut pendapat saya pengaturan seperti ini
sangat menciderai rasa keadilan dalam penegakan hukum prosedural (procedural
law) sehingga KPK akhirnya tidak mempunyai pilihan lain selain
mengikuti keputusan dewan pengawas sekalipun dianggap bertentangan dengan
prosedur maupun menjauhkan KPK dari cita penegakan hukum yang
berkeadilan. Ini penting dipersoalkan sebab ini merupakan salah satu
wilayah konflik antara pimpinan/penyidik KPK dengan dewan pengawas sehingga
proses penegakan hukum dapat menjadi terkendala. Selanjutnya keadaan kedua
dampak dari keberadaan dewan pengawas, yaitu justru dapat mengarahkan dan
membawa KPK pada kondisi penegakan hukum yang lebih berwibawa.
Sebab mungkin
saja dalam proses penegakan hukum oleh KPK dipandang oleh dewan pengawas tidak
bijak sehingga berrdampak sangat fatal dan merugikan hak-hak warga negara serta
justru menjauhkan KPK pada cita penegakan hukum yang berkeadilan. Disini
pertimbangan dan kebijaksanaan dewan pengawas menjadi sangat penting, sebab
dapat memfilter gerak langkah KPK agar tetap berada pada jalur penegakan hukum
yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi
mungkin saja kita harus akui dalam praktik selama ini proses penegakan hukum
oleh KPK dinilai offside atau keluar dari relnya (undang-undang)
sehingga merugikan hak-hak warga negara yang menjadi tahanan KPK.
Bagaimanapun,
terhadap kekurangan-kekurangan penegakan hukum yang dilakukan KPK kita harus
berlapang dada mengakuinya bahwa yang keliru perlu diperbaiki dan yang salah
harus diarahkan kembali kepada jalan yang benar berdasarkan semangat dan jiwa
undang-undang. Disatu pihak undang-undang yang baik adalah undang-undang
yang mengakomodir sebanyak-banyaknya kebutuhan hukum masyarakat, kebijakan
legislasi dibuat berdasarkan serapan bottom-up dan bukan
dipaksakan dari atas ke bawah (top-down) sehingga tidak
mengurat dan tidak mengakar dari aspirasi masyarakat. Dalam hal ini hukum
haruslah hidup dan berangkat dari kesadaran hukum rakyat serta hukum untuk
manusia bukan manusia untuk hukum.
Selanjutnya
perihal penyadapan harus seiizin dewan pengawas. Disini penting sekali satu
persepsi antara dewan pengawa dan pimpinan KPK dalam melihat dan menilai
kondisi ataupun kebutuhan hukum untuk melakukan penyadapan. Jika dewan pengawas
terlalu ketat dalam memberikan izin penyadapan dapat mempersempit ruang dan
mempersulit kinerja KPK dalam proses penegakan hukum, terutama untuk perkara
yang harus ditangani dengan sangat mendesak misalnya karena berhadapan dengan
kondisi daluwarsa, pelaku melarikan diri dan/atau dikhawatirkan menghilangkan
barang bukti, dan lain sebagainya. Namun jika dewan pengawas mempermudah atau
cenderung mengobral izin untuk melakukan penyadapan justru akan berdampak
lepasnya jaminan konstitusional terhadap hak dan kebebasan warga negara.
Selain itu, mengenai mekanisme penyadapan, saya terpaksa
harus dan hanya dapat mengutip beberapa informasi yang berkembang, dikatakan
bahwa penyadapan dapat dilakukan setelah melewati birokrasi yang berlapis
banyaknya. Disini umpanya disebut bahwa untuk menyadap dimulai dari penyelidik
ke Satgas, lalu dari Satgas ke Direktur Penyelidikan, lalu diteruskan kepada
Deputi Bidang Penindakan, melangkah lagi dari Deputi ke Pimpinan KPK, masih
perlu memasuki pintu Dewan Pengawas, setelah itu perlu gelar perkara terlebih
dahulu. Dari sini berkembang ke kekhawatiran potensial terdapat resiko bocornya
perkara ke luar gedung KPK bahkan saja bisa sampai kepada orang yang sedang
ditangani kasusnya akibat lamanya waktu proses pengajuan penyadapan. Benar tidaknya
informasi ini sayapun tidak dapat memastikan.
Tapi soal kewenangan penyadapan hanya dibatasi sampai
pada tingkat pra penuntutan, di satu pihak dapat mendorong KPK agar lebih teliti
dan hati-hati pada masa pra penuntutan untuk mempersiapkan dan menyusun
dakwaannya selengkap-lengkapnya dengan mengambil bahan-bahan selama proses pra
penuntutan itu. Kendatipun demikian tidak tertutup kemungkinan dalam praktiknya,
andailah memang demikian yang kita dengar kabarnya tentang hal ini, KPK dalam
praktik di tahap penuntutan memandang perlu untuk melakukan penyadapan lanjutan
sebab ada beberapa informasi lain yang diperlukan untuk memperkuat tuntutan
dalam surat dakwaan. Tetapi oleh karena sudah ditutup kesempatan untuk
penyadapan lanjutan itu maka berdampak kepada lemahnya dakwaan.
Lemahnya dakwaan membuat terbukanya peluang terdakwa
diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak/ontslag van alle rechtvervolging). Sedangkan kemungkinan
bagi hakim untuk mengesampingkan ketentuan seperti itu, atau dengan kata lain
hakim memberi izin kepada penuntut umum KPK sekalipun dengan alasan yang logis
dan demi kepastian dalam penegakan hukum, hakim menjadi dilematis pula sebab ia
pun nyatanya hanya corong undang-undang belaka yang mesti taati law in procedure (kecuali andai KUHP
yang baru telah disahkan). Sementara itu soal-soal seperti izin penggeledahan
dan penyitaan akan menjadi kontradiktif dengan pengaturan dalam KUHAP, meskipun
KUHAP adalah hukum acara umum bagi KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan,
penyidikan, termasuk di dalamnya kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan,
penahanan, dan penuntutan.
Tetapi hukum acara yang khusus dalam revisi
undang-undang KPK terkait izin penggeledahan dan penyitaan itu justru
menyulitkan dari yang menurut KUHAP diberi kelonggaran agar penegakan hukum
menjadi efektif dan efisien. Hal lain yang perlu dikritisi adalah kewenangan pencekalan
oleh penyelidik kepada imigrasi bagi orang yang sedang ditangani kasusnya. Bahwa
penyelidik dipersulit dalam mengambil kewenangan itu sehingga orang yang sedang
ditangani kasusnya itu dapat saja melarikan diri ke luar negeri. Kemungkinan lain
yang dikhawatirkan adalah bahwa dewan pengawas tidak memberikan izin penyadapan
sebab mendapat intervensi oleh pemerintah sebab dewan pengawas dibentuk oleh
Presiden, sehingga izin penyadapan menjadi sengaja dikecualikan kepada orang-orang
tertentu yang masih dekat atau berasal dari lingkungan istana atau bahkan orang
yang dikecualikan tersebut ternyata adalah Presiden, Wakil Presiden, Kapolri,
atau Jaksa Agung dan pejabat tinggi lainnya.
Padahal UUD 1945 kita tidak
mengenal adanya warga negara istimewa, melainkan semua warga negara sama
kedudukannya dalam hukum (equality before the law). Jika
demikian keadaannya, ini jelas melukai penegakan hukum yang dijauhkan dari cita
keadilan. Selanjutnya, perihal pengangkatan pimpinan KPK oleh Presiden. Saya tidak
dapat menerima ketentuan seperti ini, sama seperti keberatan saya untuk
pengisian jabatan Jaksa Agung saat ini dilakukan sepihak Presiden. Jika benar
pengisian jabatan komisioner atau pimpinan KPK dilakukan sepihak Presiden, maka
independensi lembaga ini akan menjadi hilang. Muncullah penegakan hukum yang
tebang pilih, hukum hanya akan ditegakkan kepada orang tertentu saja yang dipandang
membahayakan atau merugikan kepentingan rezim yang sedang berkuasa.
Dengan demikian
KPK diarahkan menjadi lembaga yang bertugas mengamankan kepentingan dan
kediktatoran rezim yang berkuasa. Terakhir tentang pengetatan wewenang
pencekalan berpergian ke luar negeri, sebaiknya ketentuan seperti ini dihapus
saja. Sebab soal pencekalan itu sudah diatur dalam undang-undang tentang
keimigrasian, tidak perlu lagi diatur kembali yang malah dapat memperkeruh
keadaan. Terakhir, status Aparatur Sipil Negara
(ASN) bagi semua pegawai KPK. Penting ditegaskan disini, apakah profesi sebagai
penyidik juga termasuk kategori pegawai KPK. Atau apakah pegawai KPK itu
dimaknai hanya mereka yang bekerja menjalankan tugas-tugas administrasi untuk
menunjang kinerja KPK. Sebab penyidik adalah profesi yang sifatnya fungsional,
ia dibutuhkan sesuai dengan bidang keahliannya yaitu melakukan tugas-tugas
penyidikan dan hal-hal yang bersangkut-paut dalam bidang tugasnya itu.
Sedangkan
pegawai yang menjalankan tugas-tugas administrasi keberadaannya adalah sebuah
keharusan dalam sebuah birokrasi atau lembaga negara. Tanpa mereka KPK tidak
akan terselenggara sebagaimana harusnya. Jadi pegawai yang menjalankan tugas-tugas
administrasi itu keebradaannya adalah keharusan kelembagaan, sedangkan
keberadaan penyidik adalah keharusan tugas dan kewenangan penegakan hukum oleh
KPK. Andai yang dimaksud pembentuk undang-undang bahwa pegawai
KPK itu adalah pegawai administrasi dan penyidik, lalu mereka semua berstatus
ASN, hal ini menjadi simpang siur. Sebab ASN sebagaimana dalam Undang-Undnag
Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai peemrintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
Pada ketentuan
umum Pasal 1 angka 2 undang-undang itu dikatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1
angka 3 dikatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
Selanjutnya Pasal 1 angka 4 bahwa Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan. Rekrutmen kedua jenis pegawai ini walaupun sama-sama ASN terdapat
perbedaan. Hal ini perlu dipertegas supaya tidak menimbulkan kesulitan teknis
dalam perekrutannya.