Karhutla Harus Ditangani
Dengan Hukum Dalam Keadaan Darurat
Dengan Hukum Dalam Keadaan Darurat
Oleh: Syahdi, SH
(Pemerhati Hukum Tata Negara)
Hari ini, Ahad (23/9/2019) Gubernur Riau menetapkan dan
mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di Provinsi Riau. Pengumuman itu
dilakukan saat konferensi pers di Media Center Karhutla Riau, Jalan Gajah Mada.
Penetapan itu dilakukan dengan berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 41
Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penetapan keadaan darurat tersebut diantaranya
berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf b yaitu “apabila hasil pemantauan menunjukan
Indeks Standar Pencemar Udara mencapai nilai 300 atau lebih berarti udara dalam
kategori berbahaya maka Gubernur
menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara di daerahnya”. Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pengumuman
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain
melalui media cetak dan/atau media elektronik”.
Jika ditelaah lebih mendasar, Peraturan Presiden Nomor 41
Tahun 1999 mengandung kelemahan ditingkat landasan yuridis dan sosiologis,
sebab dalam konsideran menimbang dan mengingat Peraturan Presiden Nomor 41
Tahun 1999 hanya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 diatur juga
mengenai penetapan dan pengumuman keadaan darurat (keadaan darurat pencemaran
udara), maka seharusnya juga mengambil rujukan kepada Undang-Undang Nomor 23
Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 ini diatur jenis-jenis keadaan darurat serta kapan dan dalam hal bagaimana
pemerintah dapat menetapkan keadaan darurat itu, termasuk menentukan
tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan.
Kelemahan tersebut dapat mempersulit
pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi karhutla, sebab tetutupnya pilihan
kebijakan lain selain daripada apa yang telah diatur dalam Perpres maupun
undang-undang lingkungan hidup tersebut. Sehingga hanya dalam batas-batas
itulah pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Riau dapat bertindak menangani
karhutla. Padahal, kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Riau perlu
penanganan yang serius apalagi menurut data terkini dari berbagai media,
kebakaran hutan dan lahan yang paling luas terjadi di Riau yaitu mencapai 49
hektar lebih. Kenyataan itu menempatkan Provinsi Riau sebagai daerah yang mengalami
kebakaran hutan dan lahannya terluas pertama se-Indonesia dibandingkan dengan
daerah lain di Indonesia. Adapun Kalimantan menempati urutan kedua luasnya
hutan dan lahan yang mengalami kebakaran yaitu berkisar 44 hektar lebih.
Karena
itu tidak dapat tidak, penanganan karhutla di provinsi Riau membutuhkan
cara-cara luar biasa dengan menggunakan hukum dalam keadaan darurat. Perlu
diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tersebut dibentuk dengan
berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Presiden menyatakan keadaan
bahaya.Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang”. Demikian
pula ketentuan pada Pasal 22 UUD 1945 ditegaskan bahwa:
(1). Dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
(2). Peraturan pemerintah
itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang
berikut.
(3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka
peraturan pemerintah itu harus dicabut.”
1.
Penetapan Keadaan Darurat Pencemaran Udara Bagian Dari Hukum Tata Negara
Darurat.
Oleh sebab penetapan keadaan darurat pencemaran udara
merupakan bagian dari Hukum Tata Negara Darurat, maka persoalan ini perlu di
dudukkan dalam pemahaman yang lebih luas dan fundamental. Sebab penetapan
keadaan darurat pencemaran udara oleh Gubernur Riau dilakukan dalam keadaan
yang tidak biasa, melainkan dalam keadaan abnormal atau emergency (darurat). Sementara itu, dalam keadaan darurat membutuhkan
penanganan yang berbeda dengan keadaan biasa, karena itu pula dalam keadaan
darurat berlaku hukum tata negara darurat atau emergency constitutional law. Pertama sekali perlu ditekankan
disini bahwa Hukum Tata
Negara Darurat harus dibedakan dari istilah hukum darurat atau emergency law yang mencakup pengertian yang lebih luas,
yaitu meliputi segala bidang hukum yang berlaku pada waktu negara berada dalam
keadaan darurat.
Sebab hukum yang berlaku dalam suatu negara, tidak hanya berkenaan
dengan hukum tata negara, tetapi juga meliputi bidang-bidang hukum yang lain,
misalnya, bidang hukum perdata, bidang hukum bisnis, bidang hukum pidana,
bidang hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Adapun penetapan keadaan darurat
pencemaran udara oleh Gubernur Riau termasuk kedalam golongan Hukum Tata Negara. Hanya persoalannya meskipun kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Riau sebagai keadaan darurat pencemaran udara, tetapi penanganannya tidak mencerminkan penanganan sebagaimana
layaknya keadaan darurat. Singkatnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
masih ditangani dengan cara-cara biasa menurut prosedur biasa dan menggunakan
hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. Padahal keadaannya sudah tidak
lagi normal, melainkan emergency atau
darurat.
Dalam praktik selama ini kita bernegara, dalam banyak keadaan
pemerintah tidak menetapkan keadaan darurat, padahal keadaan pada waktu itu
menghendaki ditetapkannya keadaan darurat termasuk penanganannya dengan menggunakan
hukum yang diberlakukan dalam keadaan darurat pula. Atau sebaliknya, pernah
pemerintah menetapkan status keadaan darurat untuk suatu keadaan tetapi
pemerintah tidak kunjung menetapkannya sebagai keadaan darurat. Beberapa kasus
dapat dikemukakan disini, diantaranya kasus di Aceh maupun luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas,
seperti yang
dikatakan Prof. Jimly
Asshiddiqie, untuk kasus tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004
maupun untuk kasus luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo
Jawa Timur yang mulai terjadi sejak 2007 seharusnya dapat lebih mudah diatasi
jika penanganannya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 Tentang
Keadaan Bahaya, namun ternyata keadaan-keadaan yang terjadi baik di Aceh maupun
di Porong oleh pemerintah pada waktu itu ternyata tidak diperlakukan sebagai
keadaan darurat.
Atau seperti keadaan kabut asap akibat kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) khususnya di Provinsi Riau dan sekitarnya yang sudah
beberapa kali terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, sehingga
menciptakan kehebohan nasional bahkan telah pula membawa dampak kepada negara
tetangga, sehingga potensial pula mengganggu harmonisasi hubungan dengan negara
tetangga kita itu, nyatanya pemerintah tidak pernah menetapkan keadaan yang
demikian itu sebagai keadaan darurat. Padahal semestinya
pemerintah menetapkannya sebagai keadaan darurat sehingga dalam penanganannya
pemerintah bisa lebih leluasa dan mudah tanpa harus memikirkan akan melanggar
hukum. Sebab dalam keadaan darurat, dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat
melanggar undang-undang bahkan UUD 1945 yang merupakan hukum yang tertinggi di
republik ini. Sebab dalam keadaan darurat berlaku asas “Ius Populi Suprema Lex”, yang berarti keselamatan rakyat adalah
hukum yang tertinggi.
Istilah
Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu dipakai sebagai terjemahan
perkataan “staatsnoodrecht” yang membahas mengenai hukum negara
darurat atau negara dalam keadaan bahaya (nood)
itu. Oleh sebab itu harus dibedakan antara “staatsnodrecht”
dengan “noodstaatsrecht”. Perkataan “nood” dalam “staatsnoodrecht” menunjuk kepada keadan darurat negara, sedangkan “nood” dalam perkataan “staatsrecht” menunjuk kepada pengertian
keadaan hukumnya yang bersifat darurat. Disamping itu, pokok soal dalam “noodstaatsrecht” adalah “staatsrecht”.
Artinya, yang dipersoalkan dalam istilah “noodstaatrecht”
itu adalah hukum tata negaranya yang berada dalam keadaan darurat.Sedangkan,
dalam istilah “staatsnoodrecht”
negaranya yang berada dalam keadaan darurat sehingga hukum yang berlaku adalah
hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. Dengan
demikian, pengertian hukum yang dimaksud dalam “staatsnoodrecht” lebih luas daripada “noodstaatsrecht’” yang hanya menyangkut hukum tata negara saja.
2. Penggolongan
Hukum Tata Negara Darurat
Jimly
Asshiddiqie menggolongkan atau mengelompokkan Hukum Tata Negara Darurat itu
yaitu kedalam:
1.
Hukum
Tata Negara Darurat Subjektif; dan
2.
Hukum
Tata Negara Darurat Objektif.
Jimly
Asshiddiqie menjelaskan bahwa, Hukum Tata Negara Darurat Subjektif atau “staatsnoodrecht” dalam arti subjektif
adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan darurat dengan cara
menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila memang diperlukan,
menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Dalam banyak literatur, istilah “staatsnoodrecht” dalam arti subjektif
ini biasa disebut “staatsnoodrecht”
saja, tanpa tambahan subjektif. Oleh karena itu, jika kita menemukan istilah “staatsnoodrecht” dalam berbagai
literatur, kita dapat memahaminya dalam konteks pengertian yang bersifat
subjektif itu. Selanjutnya beliau menuturkan, berbeda dengan pengertian hukum
tata negara subjektif atau “staatsnoodrecht” dalam arti subjektif, maka yang
dimaksud dengan “staatsnoodrecht”
dalam arti objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara dalam keadaan
darurat itu.
3. Penggolongan
Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan
Bahaya
Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Keadaan Bahaya menentukan
adanya tiga tingkatan keadaan darurat, yaitu:
1.
Keadaan
darurat perang;
2.
Keadaan
darurat militer; dan
3.
Keadaan
darurat sipil.
Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Keadaan Bahaya dikemukakan
bahwa, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau
sebagian dari Wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan
tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan
perang, apabila:
a. Keamanan
atau ketertiban umum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara
Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau
akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat
perlengkapan secara biasa;
b. Timbul
perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik
Indonesia dengan cara apapun juga;
c.
Hidup
Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata
ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
Selanjutnya,
pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa, “pengumuman
pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden”.
Dengan
demikian dapatlah dipahami bahwa, terhadap ketiga macam tingkatan keadaan
darurat tersebut diatas menghendaki harus adanya keputusan Presiden sebagai
sumber dan dasar legitimasi keadaan darurat itu. Terkait
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diatas, Jimly Asshiddiqie
menuturkan bahwa, pemberlakuan keadaan darurat itu haruslah didahului oleh
suatu pernyataan atau proklamasi resmi
yang menyebabkan keabsahan untuk dilakukannya tindakan-tindakan yang besifat
melanggar hukum biasa (ordinary law)
tersebut. Jika proklamasi atau deklarasi keadaan darurat itu tidak dilakukan,
sedangkan langkah-langkah yang diambil bersifat melanggar hukum biasa, maka
keadaan darurat demiian itulah yang disebut sebagai “emergency de facto” yang justru harus dihindari dalam setiap
negara hukum. Dalam konteks
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, keadaannya termasuk
kedalam kategori keadaan darurat sipil. Tanpa mengabaikan berbagai kenyataan di
lapangan bahwa hutan dan lahan tersebut sengaja dibakar, karhutla di Provinsi
Riau termasuk kedalam cakupan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23
Prp Tahun 1959, yakni bencana alam.
4.
Kendala dan Upaya
Yang Dapat Ditempuh Pemerintah Provinsi Riau
Memang ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Prp Tahun 1959, yang menyatakan bahwa, “pengumuman pernyataan atau penghapusan
keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden”. Tetapi ketentuan
ini telah dikesampingkan oleh Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun
1999, sehingga Gubernur Riau dapat pula menetapkan dan mengumumkan keadaan
darurat, dalam hal ini keadaan darurat pencemaran udara yang sebetulnya
konkretisasi atau spesifikasi dari bencana alam sebagaimana yang termaktub
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Sekaligus pengaturan
seperti ini dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 merupakan gejala
pemihakan pada konstitusionalitas otonomi daerah. Sebab otonomi daerah
sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.
Pasal 18
ayat (2) menyatakan, “Pemerintah daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya Pasal
18 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”. Saya katakan
ini merupakan gejala pemihakan kepada otonomi daerah sebab dengan diberikannya
kesempatan kepada Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat
pencemaran udara, maka sudah semakin mendekati gerbong yang lebih fundamental
menuju pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah
strategis untuk mengatasi bencana alam di daerahnya. Selangkah lagi Gubernur
dapat mengeluarkan semacam “Peraturan
Daerah Darurat” yang digunakan sebagai dasar legitimasi mengatasi keadaan
darurat.
Untuk di tingkat nasional, Presiden lah yang berwenang mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang (Perppu) sebagai dasar legitimasi untuk
mengatasi keadaan darurat maupun keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal
12 dan Pasal 22 UUD 1945. Meskipun tidak tegas diatur atau dilarang dalam UUD
1945 maupun dalam undang-undang, tetapi menurut logika konstitusional yang
bertahan selama ini, kepala daerah seperti misalnya Gubernur tidak berwenang
mengeluarkan produk semacam Perppu, saya menyebutnya “Peraturan Daerah Darurat”. Tidak dibenarkannya kepala daerah dalam hal ini Gubernur
mengeluarkan produk berupa “Peraturan
Daerah Darurat”, menurut pendapat saya hal itu bentuk daripada sikap yang
berseberangan dengan konstitusionalitas anutan asas otonomi daerah.
Karena itu
ketika Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada
Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara,
saya mengatakan ini merupakan gejala pemihakan kepada otonomi daerah yang
sebenarnya menurut konstitusi kita. Oleh karena Gubernur dalam hal ini Gubernur
Riau dalam menghadapi karhutla dipandang tidak berwenang menetapkan “Peraturan Daerah Darurat”, maka ini sesungguhnya
menjadi hambatan dalam penanganan karhutla yang seharusnya dilakukan dengan
cara-cara yang luar biasa untuk konteks penanganan dan dalam keadaan darurat,
sebab Gubernur pun sudah menetapkan status karhutla sebagai keadaan darurat
pencemaran udara. Tetapi Gubernur dapat melakukan terobosan hukum melalui
kebijakannya dengan mengeluarkan “Peraturan
Daerah Darurat”.
Masalah ini akan menjadi pembicaraan yang menarik nantinya
sebab akan menjadi soroton para ahli Hukum Tata Negara Indonesia. Dengan demikian
pintu menuju otonomi daerah yang sebenar-benarnya akan terbuka lebar melalui berbagai
dialog kebangsaan di republik ini. Tidak semata soal berwenang tidaknya
Gubernur mengeluarkan “Peraturan Daerah
Darurat” yang ingin dipersoalkan, seakan pembaca sekalian bertanya-tanya,
memangnya apa manfaatnya, apa untungnya kewenangan membentuk “Peraturan Daerah Darurat” itu. Sebab,
hanya dengan kewenangan mengeluarkan “Peraturan
Daerah Darurat” itulah, maka Gubernur dapat mengambil alih beberapa materi
yang berkaitan dengan sanksi dalam undang-undang tentang lingkungan hidup,
bahwa dapat diatur di dalam “Peraturan
Daerah Darurat” itu ancaman hukuman administrasi tentang pembekuan
aktivitas korporasi selama sekian waktu lamanya dan disertai dengan kewajiban
membayar ganti rugi termasuk tanggung jawab pemulihan keadaan yang ditimbulkan
dari pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi.
Juga dapat diatur bahwa kepada pelaku daripada unsur
korporasi itu diancam pidana seumur hidup mengingat parahnya dampak yang
ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan itu. Masih dapat ditambahkan pula
dengan sanksi bahwa segala keuntungan yang masih atau sedang mengalir pada
korporasi dalam menjalankan aktivitasnya sebelum dibekukan itu, dalam masa
terjadinya dampak akibat pembakaran hutan dan lahan harus diserahkan kepada Pemerintah
Daerah Provinsi Riau, menjadi aset atau pendapat lain-lain daerah dalam APBD
Riau. Pengaturan atau gagasan seperti ini memang akan terlihat bertentangan
dengan undang-undang. Tetapi dalam keadaan darurat, berlaku lex specialis derogat legi generalis,
bahwa “Peraturan Daerah Darurat” yang
notabene adalah Perda dan secara hierarkis berada dibawah undang-undang, dalam
keadaan darurat “Peraturan Daerah Darurat”
dapat mengenyampingkan atau bahkan melanggar undang-undang.
Tentang mengapa hal
seperti ini dapat terjadi sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga
melalui dibentuknya “Peraturan Daerah
Darurat” Gubernur Riau atau pemerintah Provinsi Riau mempunyai keleluasaan
untuk mengatasi keadaan darurat di lingkup wilayahnya. Sebab konsekuensi logis
dari penetapan dan pengumuman keadaan darurat adalah kemestian untuk melakukan penanganan
dengan cara-cara luar biasa dengan hukum yang berlaku dalam keadaan darurat
pula. Sebab itu selaku intelektual yang banyak bergelut dalam pemikiran Hukum
Tata Negara, saya mendorong Gubernur Riau untuk melakukan terobosan hukum
melalui kebijakannya yaitu dengan mengeluarkan “Peraturan Daerah Darurat”. Tindakan itu akan menjadi babak baru
dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern. Namun jika Gubernur Riau
tidak berani mengambil tindakan itu, upaya yang dapat dilakukan sesungguhnya
tetap ada meskipun tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat Riau yang
menderita kerugian akibat karhutla, baik kerugian materil maupun immateril.
Upaya tersebut yaitu melakukan kerjasama
dengan lembaga pemadaman kebakaran negara lain,
dengan kemampuan teknologi yang canggih tentu karhutla dapat secepatnya diatasi
sehingga udara kembali bersih dari asap dan polusi atau zat-zat yang
membahayakan kesehatan masyarakat Riau. Selain itu berkoordinasi dengan daerah
lain seperti DKI Jakarta yang semula menawarkan bantuan untuk memadamkan
karhutla di Riau, tetapi sialnya tawaran budi baik itu malah ditolak. Ini
sangat memalukan dan pemerintah Provinsi Riau terlihat sangat sombong.
Kesombongan seperti itu tidak baik dipelihara apalagi oleh selevel Gubernur.
Tetapi semua upaya itu orientasinya hanya pada pemadaman kebakaran hutan dan
lahan saja. Setelah itu merasa seakan tidak terjadi apa-apa. Disini perlukaan
rasa keadilan dialami oleh masyarakat Riau, sebab kerugian yang dialami
masyarakat Riau dirasakan tidak diperhatikan, tidak sebanding dengan kebijakan
parsial yang masih pro pada kapitalis dan menguntungkan imperialis di republik
ini.
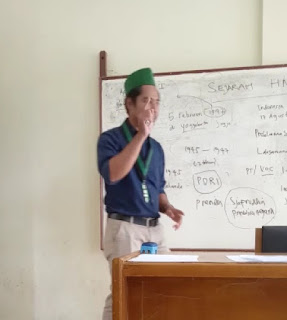




Tidak ada komentar:
Posting Komentar